Tepat pada tanggal 28 Februari 2021 lalu, sang begawan hukum di Indonesia, yaitu Bapak Artidjo Alkostar meninggal dunia. Perasaan duka, sedih, dan rasa kehilangan mendalam tentu dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang mengenal kiprah Artidjo Alkostar dalam upayanya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu, bagaimana ‘galak dan tegasnya’ Artidjo Alkostar saat menjadi Hakim Agung terutama kepada narapidana korupsi. Artidjo Alkostar bahkan sering menaikkan sanksi pidana bagi narapidana korupsi ketika mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Meninggalnya Artidjo Alkostar dihinggapi rasa duka mendalam oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terlebih ketika era pandemi COVID-19 korupsi juga masih ‘membludak’ setidaknya dengan adanya beberapa dugaan korupsi yang dikaitkan dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Selain itu, dugaan korupsi yang menghebohkan masyarakat juga terjadi pada mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara yang diduga mengorupsi paket bantuan COVID-19 serta yang terbaru adalah adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, yang nota bene terkenal sebagai salah satu Gubernur berprestasi di Indonesia.
 Masih banyaknya tindak pidana korupsi di Indonesia diperparah dengan meninggalnya ‘Sang Penjagal’ koruptor yaitu Artidjo Alkostar. Oleh karena itu, meninggalnya Artidjo Alkostar di satu sisi membuat masyarakat sedih karena sang begawan hukum yang terkenal keras dan tegas terhadap koruptor tiada. Namun, di sisi yang lain membuat para koruptor dan ‘calon’ koruptor menjadi semakin jumawa karena ‘benteng’ tangguh penghambat korupsi kini telah tiada. Tulisan ini akan berfokus pada ‘warisan’ perjuangan sang begawan hukum Artidjo Alkostar yang secara abstrak berupa paradigma hukum profetik dan secara konkret berupa penegakan hukum terhadap korupsi politik.
Masih banyaknya tindak pidana korupsi di Indonesia diperparah dengan meninggalnya ‘Sang Penjagal’ koruptor yaitu Artidjo Alkostar. Oleh karena itu, meninggalnya Artidjo Alkostar di satu sisi membuat masyarakat sedih karena sang begawan hukum yang terkenal keras dan tegas terhadap koruptor tiada. Namun, di sisi yang lain membuat para koruptor dan ‘calon’ koruptor menjadi semakin jumawa karena ‘benteng’ tangguh penghambat korupsi kini telah tiada. Tulisan ini akan berfokus pada ‘warisan’ perjuangan sang begawan hukum Artidjo Alkostar yang secara abstrak berupa paradigma hukum profetik dan secara konkret berupa penegakan hukum terhadap korupsi politik.
Paradigma Hukum Profetik: Orientasi Negara Hukum Berketuhanan sebagai Implementasi Pancasila
Gagasan hukum profetik akhir-akhir ini menjadi salah satu trend di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak Fakultas Hukum di Indonesia mulai mereduksi makna hukum menjadi sekadar Undang-Undang. Tak hayal, hukum yang seharusnya berdimensi holistik dan kontemplatif untuk mewujudkan keadilan kemudian hanya dimaknai sebagai ‘seni’ untuk mengeja dan membaca Undang-Undang. Lulusan Sarjana Hukum kemudian terbelenggu dan terlalu asyik bergelut dengan teks hukum yang formal prosedural. Konteks dan moralitas hukum menjadi terabaikan dan menjadi sesuatu ‘lahan asing’ bagi para Sarjana Hukum. Tak hayal, Sarjana Hukum tereduksi menjadi Sarjana Undang-Undang yang bersenjata teks dan melaksanakan kegiatannya sekadar membaca titik-koma dalam suatu Undang-Undang. Fenomena di atas sejatinya meresahkan berbagai kalangan termasuk Artidjo Alkostar dan beberapa pakar hukum lain mencoba mengkonstruksikan suatu paradigma hukum profetik.
Paradigma hukum profetik sejatinya mencoba melihat hukum secara lebih mendalam yang tidak hanya terbelenggu oleh aspek tekstual hukum berupa Undang-Undang. Hukum dikonstruksikan sebagai kaidah moral dan kesusilaan yang perlu dibaca secara ‘philosophical and moral reading’ tentunya dengan melihat dan mengonstruksikan nilai-nilai agama sebagai basis landasan hukum. Paradigma hukum profetik didasarkan pada tiga aspek, yaitu: humanisasi, liberasi, dan transendensi sebagaimana yang disampaikan oleh Kuntowijoyo. Aspek humanisasi menekankan pada upaya untuk menggali nilai, hakikat, serta orientasi teleologis hukum yang bertujuan memanusiakan manusia. Tujuan memanusiakan manusia harus dilihat dalam dua hal, yaitu: pertama, memanusiakan manusia dipahami sebagai upaya untuk mendudukkan manusia secara sederajat dan memiliki sifat welas asih atas sesama manusia. Hal ini sebagaimana gagasan keadilan yang disampaikan oleh Ulpianus bahwa keadilan bertumpu pada postulat, ‘Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere’ yang bermakna bahwa manusia harus hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan hak orang lain. Hal ini sebagaimana dalam konsep Agama Islam yang menempatkan setiap manusia sebagai Khalifah fil Ardhi yang menegaskan bahwa esensi setiap manusia adalah sebagai pengelola dan pemberdaya segala sumber daya yang ada di dunia, sehingga antara setiap orang memiliki kedudukan, derajat, serta hak dan kewajiban yang setara. Yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain hanyalah ketaatannya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, karena memiliki kedudukan yang sederajat dan setara, maka ‘pemimpin sejati’ antarmanusia dalam perspektif Agama Islam sejatinya bukanlah individu atau orang secara fisik. Pemimpin tertinggi adalah hukum dan sistem norma yang bersumberkan pada nilai-nilai agama dan kesusilaan di masyarakat. Sehingga, jika ada inidvidu baik itu pemimpin, rakyat jelata, atau budak sekalipun jika melanggar sistem norma baik itu norma hukum, norma agama, maupun norma etika harus mendapatkan sanksi sebagai konsekuensi tindakannya. Kedua, memanusiakan manusia harus dipahami secara ekstensif bahwa manusia perlu memuliakan dan memakmurkan setiap makhluk hidup dan alam semesta. Dalam hal ini, memanusiakan manusia harus dipahami dalam prinsip ecocracy bahwa manusia sebagai Khalifah fil Ardhi adalah pengelola yang harus mampu secara proporsional mengelola sumber daya yang ada namun juga peduli akan kelestarian alam dan lingkungan. Salah satu contoh dari penerapannya adalah prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang wajib dilaksanakan oleh setiap negara pada saat ini. Dengan demikian, prinsip humanisasi yang menekankan pada ‘memanusiakan manusia’ harus dimaknai secara luas termasuk juga bersifat welas asih terhadap semua makhluk Allah SWT, termasuk juga menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

Aspek liberasi berorientasi pada ‘pembebasan’ manusia atas berbagai sistem, dogma, serta kebiasaan yang cenderung konvensional dan hagemonik. Hal ini misalnya dalam praktik hukum bahwa hakim masih banyak yang terjebak oleh ‘kredo’ lama bahwa hakim hanya didudukkan sebagai le bouche de la lois (corong Undang-Undang). Padahal, untuk menegakkan keadilan hakim perlu melakukan langkah-langkah progresif demi memuliakan keadilan substantif, seperti melakukan penafsiran hukum dengan memanfaatkan aspek hermeneutika, semiotika, dan konstruksi hukum yang lebih progresif sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal inilah, maka aspek liberasi diperlukan dalam kehidupan manusia terutama dalam penegakan hukum. Aspek terakhir dalam hukum profetik adalah aspek transendensi yang menekankan pada pemanfaatan spiritual and moral reading of law sehingga nilai-nilai agama yang dianut, dihayati, serta dilaksanakan di masyarakat perlu mendapatkan jaminan hukum sekaligus dijadikan rujukan pada praktik hukum di pengadilan. Hal ini penting karena Indonesia merupakan religious nation state yang mendudukkan hukum agama dan hukum negara layaknya saudara yang saling berhubungan. Sehingga, hukum negara dapat disinari dan dipancari oleh nalar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam praktiknya, Artidjo Alkostar sering menggunakan paradigma hukum profetik dalam menangani kasus hukum, terutama korupsi saat masih menjabat sebagai Hakim Agung. Bahkan, Artidjo Alkostar sering menaikkan hukuman pidana para pelaku korupsi ketika mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Jika menggunakan logika hukum secara legal-formal, tentu hal ini tidak dapat dilakukan, tetapi dengan ‘senjata’ hukum profetik, Artidjo Alkostar sering membuat koruptor menjadi takut bahkan mencabut berkas kasasi ketika tahu majelis hakimnya ada nama Artidjo Alkostar.
Penegakan Hukum Korupsi Politik: Berpilar Profetik dan Bernalar Holistik
Salah satu ‘magnum opus’ dari Artidjo Alkostar adalah pemahamannya tentang korupsi politik yang secara proses maupun sanksi harus mendapatkan perhatian yang lebih. Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga tipe korupsi yang menjadi fokus dari Artidjo Alkostar. Tiga tipe korupsi tersebut yaitu: korupsi etik, korupsi pragmatik, dan korupsi sistemik. Korupsi etik berkaitan dengan perilaku dan karakter individu pejabat publik yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kode etik seperti datang terlambat, menunda-nunda pekerjaan, hingga merasa lebih benar dengan dalih adanya prinsip ‘senioritas’ di institusi. Korupsi jenis ini sejatinya sulit dilacak dan dibuktikan menurut proses hukum yang patut. Korupsi etik hanya bisa ditegakkan dengan sanksi etik termasuk juga pendidikan karakter yang berkala bagi pejabat publik untuk mengabdikan diri sebagai pelayan sekaligus teladan masyarakat. Sehingga pejabat publik akan terhindar dari perbuatan tercela yang tergolong sebagai korupsi etik. Selanjutnya adalah korupsi pragmatik yang menurut hemat penulis merupakan korupsi yang terjadi karena adanya maladministrasi, proses administrasi dan pelayanan publik yang terlalu berbelit-belit, maupun karakter pejabat publik yang masih berkarakter feodal dengan pola hubungan patron-klien. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian bersama karena seringkali pejabat yang bersangkutan menawarkan privilege khusus ke masyarakat atas pelayanan administrasi yang lama dan berbelit-belit tentunya dengan imbalan dan harga tertentu. Korupsi pragmatik sejatinya dapat diantisipasi jika penataan sistem administrasi publik dapat dilaksanakan secara baik, efektif, dan efisien, tentunya dilengkapi dengan moralitas pejabat publik yang taat pada kode etik dan kode perilaku jabatan. Terakhir adalah korupsi sistemik yang dalam bahasa Artidjo Alkostar merupakan korupsi politik yang berkaitan dengan elite-elite politik,ekonomi, maupun oligarki yang berselingkuh dengan kekuasaan. Dalam perspektif pelanggaran HAM berat (Gross Violation of Human Rights), maka korupsi sistemik ini telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif sehingga layak mendapatkan hukuman maksimum. Salah satu contoh korupsi sistemik dan memiliki orientasi politik adalah korupsi e-KTP yang melibatkan elite politik, pengusaha, bahkan beberapa pihak di luar negeri.

Pada praktiknya, Artidjo Alkostar sering menghukum maksimum para koruptor terutama yang berkaitan dengan korupsi sistemik yang dalam istilah Artidjo Alkostar disebut sebagai korupsi politik. Tak heran jika Artidjo Alkostar ‘ingin’ menghukum mati koruptor jika seandainya ketentuan Undang-Undang yang berlaku memperkenankan hal tersebut. Hal ini dikarenakan korupsi politik yang bersifat sistemik tersebut bisa menjadi pemicu lahirnya tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pemalsuan dokumen, dan berbagai tindak pidana lainnya. Dampaknya pun tidak main-main, kerugian negara yang besar juga berdampak pada masyarakat miskin yang kurang beruntung yang seyogianya uang negara yang dikorupsi tersebut bisa memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan kurang beruntung.
Berdasarkan uraian di atas, Artidjo Alkostar telah mewariskan semangat hukum profetik dalam menumpas tindak pidana korupsi yang semakin masif terjadi. Artidjo Alkostar layak menjadi uswatun hasanah bagi masyarakat, khususnya calon penegak hukum yang masih dalam proses pembelajaran. Mengutip pesan Artidjo Alkostar bahwa, “Kebenaran dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak dapat diajarkan, tetapi harus dihidupkan”. Yang menjadi pertanyaan, mau dan mampukah kita menghidupkan semangat keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan?. Mungkin nurani pembaca yang budiman yang akan menjawabnya. Terlepas dari itu semua, wafatnya sang begawan hukum Artidjo Alkostar tidak perlu kita ratapi secara berlebihan, harusnya kita lebih khawatir dan meratapi apabila hukum dan keadilan wafat dari Bumi Indonesia dan tidak ada satupun yang berani menegakkan hukum dan keadilan. Semoga tulisan ini menjadi inspirasi bagi semua bahwa meneladani Artidjo Alkostar adalah pada semangat untuk berani mendobrak serta memperbaiki citra hukum bangsa yang kian terpuruk. Pada pundak pemuda dan penegak hukum di Indonesia saat inilah ‘Artidjo Alkostar muda’ akan lahir dan berupaya menegakkan hukum secara paripurna. (EN)
Biografi Penulis

Dicky Eko Prasetio
Mahasiswa aktif jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Untuk mengenal lebih jauh tentang penulis dapat menghubungi e-mail pribadinya dickyekoprasetio@gmail.com

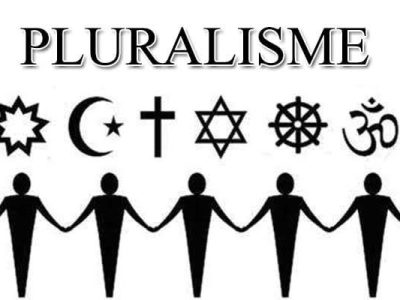








No comments