Bagi umat Islam, pelaksanaan hari raya Qurban (‘idul adlha) bukan hanya bicara soal spiritualitas, taqarrub ilallah, ataupun aksiologi ukhrowi yang menjanjikan. Qurban lebih dari itu semua, nilai historis yang tidak habis-habis digali, setiap ditala’ah muncul pengetahuan baru, ditala’ah lagi tersembul pemahaman logis, begitupun seterusnya. Begitu juga nilai sosial yang terkandung, semakin dikaji lebih dalam, selalu tersirat hal-hal baru, muncul gambaran-gambaran sosial, bahkan telah sampai pada analogi “fastabiq al-khoirot” yang pada akhirnya menyisir pada partikel-partikel kecil sistem sosial berada tepat garis pemisah antara ikhlas dan riya’.

Jika seiisi masjid menangis mendengar kisah Nabi Ibrahim, kiranya wajar. Atau tersentuh hatinya saat mengingat-ingat pengorbanan Nabi Ismail, itu juga lumrah. Ibadah yang diluar nalar manusia normal, lepas dari kekang huministik dan sepintas bersifat irrasional. Seolah, historisitas ibadah qurban, selain ritual ibadah tertua di dunia ini, juga menggambarkan bahwa totalitas penghambaan berada jauh di luar zona muamalah, kemanusiaan dan hal duniawi lainnya yang dimiliki manusia. Memantik pesan mendalam tentang segala yang kita miliki; harta, anak, jabatan, hanyalah titipan yang sewaku-waktu hilang fatamorgana.
Kita simak ulang percakapan hebat antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang tergambar dalam surat as-Shaffat ayat 102-109. Ketika Nabi Ibrahim menerima perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, “bagaimana menurutmu, wahai Ismail”, Ia menjawab “Wahai ayah, jika itu perintah Allah laksanakanlah, saya sabar dan ikhlas”. Bagaimana kalau kita berada di posisi keduanya dengan iman dan tingkat keikhlasan yang kita miliki sekarang? Tiba-tiba saja, omset bisnis kita merosot tajam dan kekayaan hilang sekejap mata, apa yang terjadi?; stres dan emosi tinggi. Ini tentu baru harta yang diambil, bagaimana kalau nyawa anak, saurada, cucu?
Algazel (cara orang Barat memanggil al-Ghazali), menyebut jawaban kepasrahan Nabi Ismail adalah perilaku supranatural bentuk cinta untuk diakui oleh Rabb Nya. Sedangkan keikhlasan Nabi Ibrahim digambarkan sebagai totalitas ego manusia sebagai wujud ketaatan non logic. Suatu kondisi dimana manusia berada pada tingkat super ego yang lepas dari seluruh sel-sel hewani, melayang bak ruh ilahiyah dengan perasaan bahagia tiada tara. Fenomena sosial kemanusiaan yang tidak dapat diteliti oleh metode penelitian modern, apapun bentuk hipotesisnya. Penyatuan akut antara konsepsi an-nafs, al-ruh, al-aql dan al-qalb.
Disembelih, konotasinya adalah “dibunuh” secara abnormal. Pemakaian kata yang disyariahkan untuk binatang agar halal dimakan. Sepintas, hal itu bertentangan dengan syariah Islam. Bagaimana mungkin, Allah memerintah sesuatu yang tidak humanis? Apalagi, ini menyembelih anak sendiri yang jelas-jelas amanah dari-Nya. Keraguan ini jua menghantui Nabi Ibrahim setiap saat. Beliau berada diantara yakin dan tidak yakin. Sehingga beranggapan kalau mimpi tersebut datang dari syaitan. Tapi apa mungkin, syaitan berani masuk ke dalam mimpi seorang Nabi? Secara logika tidak, itu hanya keraguan Nabi Ibrahim saja yang diarahkan pada Syaitan. Dari saking tidak percaya pada mimpi tersebut. Banyak pakar berpendapat, seperti al-Kindi, al-Farobi dan at-Tobari, bahwa perintah di luar syariah hanya terjadi pada manusia berkekuatan supratural, totalitas penghambaan dan kaffah.
Bagi manusia normal, peristiwa ini adalah ujian di luar nalar. Dalam ilmu psikologi, oleh Ipan Pahlov (w. 1936) disebut dengan konsep the unconditioned or unliearned stimulus, perasaan melupakan seluruh yang kita miliki tanpa beban dan stimulus (harapan, kepentingan). Benar saja, patut direfleksikan. Berpuluh tahun lamanya, Nabi Ibrahim mengharap keturunan dari Sarah, namun belum juga dikaruniai. Hingga akhirnya diusia 90 tahun menikah dengan Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail besar, wajah semringah tak dapat disembunyikan. Saat bahagia itulah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbanka anaknya. Lalu apa yang dijawab Nabi Ibrahim? Beliah menyembelihnya kendati kemudian Allah mengganti dengan seekor domba. Dahaga bertahun-tahun menunggu keturunan, setelah sejenak tersirami, kembali diminta oleh yang Haq.
Anak, harta dan jabatan. Menyetir teori prioritas Adam Smith (w. 1790) tingkat berharga dan keengganan manusia tertinggi berurutan anak dulu, harta kemudian jabatan. Anak, tidak dapat dihargai dengan harta maupun jabatan. Bahkan kecintaan orang tua kepada anaknya, ditambah dengan kondisi bertahun-tahun menanti, dalam ilmu tasawwuf diistilahkan dengan hakikat mahabbah, punjak kecintaan yang sangat tinggi. Namun kemudian, Allah meminta untuk dikorbankan.
Patut direfleksikan, apalah harta kekayaan yang kita miliki, kebahagiaan fatamorgana yang sebenarnya fana, kenyamanan karir yang saat ini atau akan datang kita harapkan, toh semua hakikatnya milik sang haq, Tuhan semesta alam. Kita baru diperintahkan untuk menyisihkan harta kita untuk dbelikan seekor sapi atau kambing, kemudian diqurbankan untuk dinikmati semua fakir miskin. Namun terkadang hal demikian, sangatlah berat. Bagaimana kalau anak? Masyaallah, wallahu a’lam bisshawab.Salam… (@D)

Saoki, MHI*
*Saoki, MHI adalah Dosen ekaligus Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya

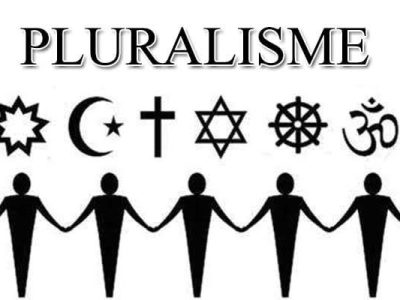







No comments