“Mbah… Bangun Mbah!”, teriak seorang laki-laki usia berbadan gempal sembari menggoyang-goyangkan tubuh seorang kakek. Kakek tersebut tergeletak lemas di tanah tak sadarkan diri. Orang-orang mengerumuninya membentuk lingkaran bak melihat harta karun. Berdesakan. Salah seorang anak kecil berumur enam tahun menangis mirip seseorang yang ditinggal kekasihnya. Mungkin ia adalah cucu dari kakek tersebut. Sementara itu ada nenek dengan tongkat sebagai kaki ketiganya tak mau ambil pusing untuk berbaur melihat sang kakek. Nenek itu memilih duduk kursi bambu. Diam mematung. Orang-orang semakin ramai datang sampai-sampai memenuhi jalan. Tak ada senyum tersimpul, yang ada hanyalah air mata yang membalut suasana di rumah tersebut.
“Duh Gusti Alloh. Mbah… Aku ora rela, ndak ikhlas Mbah. Jangan tinggalkan kami. Nanti siapa yang akan menggantikan Mbah. Ndak ada generasi muda yang sempat belajar dengan Mbah!”, ucap seorang bapak berjenggot. Dilihat dari cara berpakaiannya, bapak itu adalah seorang Kyai.
Di samping bapak tersebut, terlihat ada wanita muda yang tengah meggendong bayinya sembari berkata “Kasihan sekali kamu nduk, tidak ada lagi yang akan membacakan untukmu!”, ucap ibu muda tersebut sesekali menyeka air mata.
…
Bulan basah sudah datang sejak lima hari yang lalu. Akibatnya, sepanjang jalan yang mengangga di Dukuh Grogah penuh dengan kubangan air. Baru pagi ini nampak jelas sorot mentari terpantul mengenai dedaunan dan reranting. Embun tetap terjaga dalam pucuknya. Semua sudah kembali beraktifitas tanpa payung, topi bambu, ataupun jas hujan. Ayam-ayam kembali mematuk-matuk tanah, kucing kembali menangkap laron-laron yang tersebar di atas jalan bersemen, anak-anak sudah kembali bersekolah, para petani sudah kembali ke sawah, ibu-ibu juga sudah kembali berbelanja di tukang sayur. Sangat antusias para ibu tersebut memilih-milih sayuran yang bagus. Ini dikarenakan sang tukang sayur absen sejak lima hari yang lalu.
“Wah… Sawinya segar-segar. Kangkung juga. Tomat, kacang, jeruk, semuanya terlihat segar ini.”, ujar Bu Kari warga Dukuh Grogah.
“Lho Pak, kok jajannya sudah habis?”, sambung Bu Tumijem.
“Iya Bu. Mohon maaf kan ini saya sudah lama ndak bakulan.”, timpal Pak Slamet sebagai tukang sayur,
“Jajannya cari di pasar saja Bu. Banyak di sana.”, ucap Bu Katmi sembari memberikan uang belanjaan.
“Masalahnya, ini buat orang-orang yang membantu pindah sound system. Nanti sore baru saya beli. Kan acaranya nanti malam.”, jawab Bu Tumijem. Ia terus menggaruk-garukkan kepala karena uban dan kutu rambut yang merajai kepala beliau. Kutu-kutu itu baru hijrah ke kepala Bu Tumijem sejak anaknya terkena kutu dari kucingnya.
“Oh iya, di rumah Bu Tumjem kan ada acara nanti malam. Mitung bengi kan Bu ? Sudah ndak sabar ingin melihat pembacaan kidung dari Mbah Djalil.”, ujar Bu Wonijem.

Mitung bengi adalah tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari ketujuh kelahiran bayi. Tradisi ini masih dilakukan di beberapa wilayah Jawa namun, dengan nama yang berbeda-beda. Di sebagian wilayah Kabupaten Trenggalek sendiri tradisi ini diselingi dengan maca’. Maca’ ialah pembacaan tembang macapat pada anak yang berumur 7 hari. Mbah Djalil ialah satu-satunya sosok yang menyebarkan tradisi ini. Faktor yang mempengaruhi ialah beratnya bacaan yang terdapat dalam kitab kuno dan banyak masyarakat yang tidak paham akan isi dalam kitab. Sebelum dilakukan pembacaan tersebut didengungkan pula shalawat Nabi. Tujuan dari shalawat ini adalah agar kelak anaknya bisa menghadapi kehidupan dengan baik dan selalu ingat kepada Sang Maha Pencipta.
“Ndak bisa dibayangkan kalau Mbah Djalil sudah meninggal. Pasti anakku nanti tidak ada yang membacakan tradisi yang langka itu.”, ucap Sukati menimpali. Perutnya semakin besar. Ia tinggal menunggu lahirnya sang anak. Kata dokter dan dukun yang ada di dukuh tersebut diprediksi anaknya akan lahir pada hari Jumat depan.
“Hus! Kamu ini bicara apa? Tidak baik mendoakan orang cepat meninggal seperti itu. Apalagi Mbah Djalil, beliau adalah orang yang disegani masyarakat. Bukan hanya di Dukuh Grogah, bukan hanya di Desa Manggis. Bahkan sampai wilayah Trenggalek. Kamu ini hamil masih saja mulutnya ndak bisa dikontrol. Awas saja nanti kalau sampai murid-murid jaranan asuhan Mbah Djalil dengar, celaka kamu!”, sela Bu Katmi.
“Bukan seperti itu maksud saya Bu Katmi. Tapi, saya hanya melihat kenyataan. Mbah Djalil dulu dan sekarang itu berbeda. Dulu, Mbah Djalil masih kuat memimpin sanggarnya. Kuat untuk pencak silat, kuat menjadi dalang, kuat berjoged bersama sinden. Nah, sekarang untuk menyeruput wedang saja terlihat berat. Seperti mengangkat beban berton-ton. Mbah Djalil itu kepikiran istrinya yang sekarat ditambah lagi dengan adanya selisih paham dengan mantunya sendiri.”, ujar Bu Sukati. Ia kembali mengelus perut besarnya.
“Astaghfirullah… Sudah ibu-ibu jangan membicarakan orang di pagi hari. Itu sungguh tidak baik. Saya mau pulang dulu, persiapan untuk nanti malam. Ayo Rin kita pulang.”, ajak Bu Tumijem kepada Ririn yakni tetangga terdekatnya.
Pemandangan seperti demikian sudah sering terjadi di tukang sayur. Selalu saja ada topik yang diperbincangkan. Tukang sayur hanya tertawa kecil dan menggeleng-gelengkan kepala menyaksikan perdebatan kecil. Ia menganggap sebagai hiburan. Itulah mengapa tukang sayur itu selalu menyisakan bahan dagangan di Dukuh Grogah tersebut.
***
Siang baru saja reda. Mengucapkan salam pada matahari terakhir hari Jumat ini. Rona oranye agak sedikit berkabut di langit barat. Tipis saja. Kubangan air masih terlihat di beberapa sudut jalan. Daun-daun menggigil kedinginan tak mampu melindungi kelopak bunga yang terpaksa gugur tersiram hujan lima hari lalu. Cacing, lintah, rengit menggeliat berlomba muncul ke permukaan. Beradu dengan kutu air yang siap mencari kaki-kaki tak beralas.

Mbah Djalil berjalan dengan hati-hati. Tangan kanannya memegang dahan, ranting, daun, dan apa saja yang berada di samping jalan. Rumah Bu Tumijem letaknya paling bawah. Masalah jalan, jangan ditanya lagi. Sangat licin ditambah adanya lumut yang tumbuh di antara garis jalan bersemen tersebut. Mbah Djalil masih semangat seperti hari biasanya. Sepertinya beliau sudah tak sabar untuk kembali berkarya lewat kidungnya. Dalam hatinya ia berharap ada anak muda yang belajar seperti dirinya. Ia paham betul jika sebuah kidung bukanlah mudah untuk dwariskan. Kata kidung itu pun sudah akrab dengan beliau. Maka, ia mengakui kalau eksistensi dirinya sangat berharga di masyarakat. Ia berhenti sejenak. Pikiran mengambil alih tubuhnya. Teringat akan istrinya yang sedang sakit. Besok, ia berencana memeriksakan ke dokter dan mengurut kaki sang istri ke tukang urut terkenal namanya Mbah Kerno. Ia tak ingin istrinya merasakan sakit sejak tiga bulan terakhir. Satu-satunya orang yang paling mendukungnya berkarya adalah istrinya. Mantu dan anaknya sangat menentang keras.
Mantuya adalah seorang Kyai, lulusan pondok pesantren tradisional. Pondok yang amat terkenal di Kecamatan Panggul. Ia menganggap apa yang dilakukan Mbah Djalil termasuk perbuatan syirik. Walaupun ia paham Mbah Djalil dapat terkenal dengan karya kidungnya sampai mendapat penghargaan kabupaten serta masih bisa mencari uang di usia 62 tahun. Ia tetap pada pendiriannya yakni syirik. Ia pun tak suka dan sering pulang ke desa lain yaitu rumah keluarganya apabila ada hajatan yang berbau kental dengan tradisi setempat. Padahal, Mbah Djalil sebenarnya juga sseorang Kyai.
Mbah Djalil terbangun dari lamunannya. Ia bergegas ke rumah Bu Tumijem. Rumah Bu Tumijem sangat ramai. Ada yang sibuk di dapur, ada yang menyalami tamu, ada yang menggerombol di kamar untuk melihat sang bayi, ada yang berfoto-foto, ada yang membawa lengser sebagai tempat kopi dan teh serta makanan untuk disuguhkan kepada sesepuh di ruang tamu. Anak-anak berlarian. Sesekali mereka ditegur oleh orang tuanya. Begitulah suasana di Dukuh Grogah yang masih terjaga sikap madaninya.

Beberapa anak muda mengecek mikrofon dan mengatur volume. Pertanda pembacaan kidung akan segera dimulai. Mbah Djalil membuka kitab kuno, tulisan kitabnya nampak seperti aksara Jawa, nampak pula seperti huruf Arab. Mungkin itu adalah aksara pegon. Kitab seperti itu tidak pernah ada yang punya. Di sampingnya ada keris, surat yasin, dan rempah-rempah. Itulah piranti yang wajib ada. Mbah Djalil pun menarik napas panjang. “Ana kidung…..”, bibirnya bergetar saat menyairkan puisi itu. Andai saja pemerintah mengetahui apa yang dilakukan Mbah Djalil ini merupakan suatu bentuk melestarikan budaya Jawa. Sudah sepatutnya ada anak muda yang meneruskan karyanya. Jika diperhatikan betul, lirik-lirik yang disyairkan oleh beliau berisi tentang apa yang terjadi dalam kehidupan manusia dan bagaimana cara menjalaninya berdasarkan perintah agama.
Seekor burung kekuningan melintas tidak jauh di atas rumah. Memindahkan tubuh mungilnya dari sebatang pohon ringin ke dahan pohon pinus, seolah memamerkan kebebasan yang dimilikinya. Hari ini tepat sesuai rencananya. Mbah Djalil dan keluarga akan membawa istri Mbah Djalil untuk berobat. Ia berharap kali ini dapat segera pulih. Hari ini pula, Sukati melahirkan anak perempuannya. Lagi-lagi prediksi sang dokter dan dukun salah. Jumat tepatnya Mbah Djalil kembali melantunkan karya suaranya lewat kidungnya. Tak tanggung-tanggung, kabarnya akan ada syuting di rumah Sukati. Mudah-mudahan dengan adanya syuting ini momen Mbah Djalil dapat terabadikan.
Jumat ini tak seperti biasanya. Ada pemandangan hangat dari keluarga Mbah Djalil. Mantu dan anaknya yang dulu menentangnya. Entah kenapa hari ini mengijinkan. Apa dikarenakan adanya syuting atau apa yang jelas sebagai bentuk syukur Mbah Djalil selalu mengucapkan dzikir di pagi ini. Bukan karena alasan itu saja, tetapi istrinya sudah mulai sembuh walaupun masih memakai tongkat untuk berjalan.
Namun, sejak tiga hari yang lalu kondisi kesehatan Mbah Djalil nampak lemah. Walaupun ia masih bisa bergurau dengan anak kecil. Pagi ini saja ia telah membuat anaknya Bu Katmi menangis gara-gara ditakut-takuti cacing. Ia tak dapat menyembunyikan batuk yang menyerangnya. Demi bisa datang di acara Sukati, Mbah Djalil mengajak ponakannya yang bernama Sutamkin untuk membeli obat. Padahal, anggota keluarga sudah melarang untuk dibonceng tetapi Mbah Djalil memaksa. Ia memang tak bisa sembuh apabila tidak membeli obat sendiri. Itu sudah menjadi rutinitasnya. Mau tidak mau anggota keluraga menuruti kemauan Mbah Djalil.
***
Suara tangis tak dapat ditahan Sutamkin. Ia beralih duduk di kursi ambulance. Suara sirinenya membuat mobil dan sepeda di depannya harus mengalah. Ia memperhatikan wajah Mbah Djalil yang tersenyum. Ia tak menduga kalau kakek kesayangan semua orang itu pergi karena jatuh dari motor. Pandangan Sutamkin kabur. Mbah Djalil sudah tiada bersama karyanya. Salam… (@D)

Dewi Trisna Wati*
* Dewi Trisna Wati adalah pemikir muda yang sudah menghasilkan karya tulis di berbagai media dan juga beberapa Antologi bertaraf nasional, Mahaiswa Aktive PAI IAIN Kediri. (email: dewitrisnawati135@gmail.com).

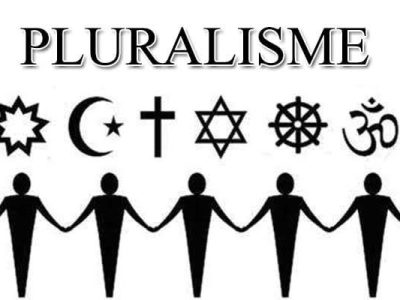








No comments