Matahari kembali menyombongkan sinarnya di sisi timur langit. Menyiramkannya dengan lembut ke seluruh persada. Tak terkecuali pada rerumputan yang mengerumuni latar, bak hiasan. Angin sepoi-sepoi dengan lembut menggoyangkan pepohonan, menyibak debu di jalanan, dan menggelitik bulu hidungku. Memberikan aroma natural dari tanah dan air pegunungan – hal yang tak bisa kudapatkan kala aku masih di kota. Begitu rindu dengan kenikmatan tiada banding ini.
“Eh kamu kenapa masih di sini bukannya siap-siap. Kita kan harus ke rumah Mbak Yuyun, bantuin acara walimatul khitan buat si bungsu,” ucap ibu membuyarkan lamunanku.
Entah kenapa rasa malas mendadak memasung tubuhku. Aku pun bingung sejak kapan aku tak menyukai acara yang membuat keluarga besarku berkumpul, terlebih di rumah Mbak Yuyun. Sudah menjadi hobinya untuk menguliti kehidupan orang lain, bahkan aku sepupunya sendiri pun menjadi topik menarik untuknya setiap kali kami berkumpul.
Berat kaki ini melintasi jalanan, langkah demi langkah menimbulkan bunyi gesekan yang berasal dari perpaduan antara sandal jepitku, kerikil, dan aspal. Ibu melangkah 2 meter di depanku, menyuruhku berjalan lebih cepat.
Belum sempat mengucap salam, Mbak Yuyun sudah melontarkan celoteh pertamanya untukku.
“Loh Naila sudah pulang rupanya. Kok gak main ke sini? Masa nunggu ada acara keluarga dulu baru main?” ujarnya.
Aku membalasnya dengan senyuman tipis sembari mengulurkan tangan untuk bersalaman. Mata-mata yang sebelumnya fokus memperhatikan cerita Mbak Yuyun tentang kehidupan orang lain kini berganti mengintimidasi kehadiranku. Salah satu dari mereka meraih tanganku dan menyuruhku bergabung dengan gerombolan mereka. Mataku memandang punggung Ibu yang melangkah menuju dapur, rasanya ingin berteriak meminta tolong. Kesehatan mentalku tak lama lagi akan jatuh sakit. Masing-masing dari mereka mengupas kehidupan seorang gadis di desa sebelah dengan versi yang beragam. Berawal dari julukan gadis nakal, gonta-ganti pasangan, sampai hamil kembar tiga di luar pernikahan. Cemooh mereka sangat menggangguku, bukan karena aku tidak terima gadis itu dicela, tapi aku sadar sebentar lagi aku akan menggantikan posisi gadis itu sebagai bahan pembicaraan mereka.
 “Dengar-dengar Naila ini kuliah di kota ya? Bidang apa, Nai? Biayanya mahal?” ujar salah satu dari mereka yang sedari tadi matanya tidak beralih dari memandangku.
“Dengar-dengar Naila ini kuliah di kota ya? Bidang apa, Nai? Biayanya mahal?” ujar salah satu dari mereka yang sedari tadi matanya tidak beralih dari memandangku.
“Ah si Naila ini dapat beasiswa, jadi ibunya gak mengeluarkan biaya apapun. Jurusan apa itu aku lupa, Bahasa Indonesia ya?” jawab Mbak Yuyun yang membuatku sedikit merasa dibanggakan.
“Ya ampun kamu ini belajar Bahasa Indonesia aja sampai pergi ke kota, aku juga bisa loh ngajarin kamu Bahasa Indonesia.”
Deg. Perasaan bangga secepat kilat berubah menjadi rasa kecewa. Kenapa hal seperti itu harus ditertawakan, ini bercandaan yang menurutku sangat tidak lucu. Ucapannya membuat darahku mendidih, dengan sangat berat hati aku ikut meringis menonton tawa mereka yang membosankan. Sudah jatuh tertimpa tangga, belum sempat hati ini beristirahat dari rasa amarah, mereka sudah memuntahkan pertanyaan yang lain. Sekarang kerja dimana? Gajinya berapa?
Mendengar jawaban Mbak Yuyun bahwa aku belum bekerja, membuat mereka lebih maju untuk menguliti kehidupanku. Mereka mengatakan bahwa kuliah di kota tidak ada gunanya jika aku belum bekerja. Ya Allah, belum juga satu minggu aku pulang kampung.
“Nai, kamu di kota 4 tahun lamanya. Paling enggak usahalah dulu cari kerja. Bantuin ibumu cari uang. Buat apa kuliah jauh-jauh kalau masih jadi pengangguran? Kalau tahu begini kan lebih baik kamu lulus SMA langsung menikah. Ingat temanmu si Ningsih? Dia sudah menikah sama anak kades. Sahabatmu Linda juga sudah punya 2 anak. Lilis aja sekarang udah punya minimarket sendiri tanpa kuliah. Kalau kamu gak kerja mending nikah aja. Percuma kan gak bisa bantuin orangtua dengan gelar sarjana, malah menyusahkan. Jangan ngikutin orang kota yang berpendidikan kalau latar belakangmu hanya anak seorang petani jagung.” Ujar Mbak Yuyun membuat air mata yang sedari tadi kutahan kini lolos dari bendungannya.
 Entah bagaimana ekspresi yang tergambar ketika aku berpamit meninggalkan gerombolan itu. Melarikan diri menuju teras yang sepi. Jilbab yang terjuntai menggantikan tugas tissue yang mengeringkan air mataku. Namun kemudian kubiarkan air mata ini menderas demi sedikit menetralkan perasaanku. Aku suka hening, mengunjungi ruang imajinasi dan mengukir kisah yang kukehendaki. Rasanya lebih nyaman berada di dunia sendiri.
Entah bagaimana ekspresi yang tergambar ketika aku berpamit meninggalkan gerombolan itu. Melarikan diri menuju teras yang sepi. Jilbab yang terjuntai menggantikan tugas tissue yang mengeringkan air mataku. Namun kemudian kubiarkan air mata ini menderas demi sedikit menetralkan perasaanku. Aku suka hening, mengunjungi ruang imajinasi dan mengukir kisah yang kukehendaki. Rasanya lebih nyaman berada di dunia sendiri.
“Mau ikut ibu ke pasar?” Ibu bertanya dari samping. Aku berdiri perlahan menunjukkan jawaban.
Melihat gelagatku yang berbeda, ibu hanya diam berjalan senada disampingku. Ibu tidak mengusikku untuk beberapa saat. Membiarkan suasana hening ini sedikit menenagkanku.
“Apa kamu menangis karena ucapan Mbak Yuyun?”
Aku menjawabnya dengan anggukan. Aku yakin Ibu pasti mendengarnya. Beruntung aku tak perlu menjelaskan.
“Ibu boleh bercerita, Nai?” Ibu bertanya lembut. Aku mengangguk sebagai bentuk persetujuanku.
“Coba kamu lihat angin di sekitar kita sekarang. Apa bisa kamu menemukannya? Apa bisa tanganmu menggenggamnya? Apa pernah sedetik saja kamu merindukannya? Ibu yakin jawabannya tidak. Kebanyakan manusia memang gitu. Hal yang sangat sederhana seperti angin hampir tidak pernah mereka pikirkan walaupun tidak sedetikpun angin meninggalkan mereka. Bagaimana jika dibandingkan saat kita memejamkan mata, tarik napas perlahan lalu hembuskan. Maka, esensi angin akan lebih mudah untuk kita sadari. Angin juga bisa menunjukkan keberadaannya dengan menerbangkan benda ringan seperti debu yang bisa saja masuk ke mata, atau menerbangkan dedaunan yang jelas terlihat oleh mata, atau bahkan menerbangkan benda-benda berat seperti angin topan yang menerbangkan pepohonan, genting-genting rumah, mobil, dan sebagainya. Tapi apakah hembusan angin ada hanya untuk membuat manusia menyadari esensinya? Bagi manusia yang memiliki iman di dalam hatinya, jawabannya jelas tidak. Orang yang beriman memiliki tugas untuk meng-iqra’. Membaca, memikirkan, dan menafakurkan. Itu sudah jelas kita pelajari dalam kitab suci kita sebagai ayat pertama yang diturunkan oleh Allah. Ketika kita benar-benar meng-iqra’, maka akan kita temukan bahwa segala yang dilakukan oleh angin adalah kehendak Allah untuk menunjukkan kekuasaan-Nya. Itulah yang disebut takdir.”
Ibu menghela napas dalam-dalam sebelum melanjutkan kalimatnya.
“Angin menerima takdirnya dengan penerimaan terbaik. Dia menjalankan segala perintah dengan ikhlas. Bayangkan jika angin menentang perintah. Misalnya, dia berhenti untuk berembus karena lelah, maka manusia akan mati, hewan-hewan mati, tumbuhan mati, bahkan bumi pun bisa mati. Tapi, karena angin menerima takdirnya dengan penerimaan terbaik, hal sederhana sepertinya malah memberikan manfaat yang begitu besar untuk kehidupan di bumi ini. Jadi, apa sekarang kamu bisa mengambil pelajaran dari sini?” Ibu bertanya padaku yang masih mencoba untuk mencerna.
Seperti mendapat hidayah, aku bisa mengerti apa maksud Ibu dengan hati dan pikiran yang positif.
“Hal sederhana seperti angin, ketika menjalani takdirnya dengan ikhlas, maka keajaiban akan muncul dan memberi manfaat pada banyak hal.Jadi, jika sampai sekarang kamu belum mendapatkan pekerjaan, itu adalah sebuah takdir yang harus kamu terima dengan ikhlas dan jalani dengan penerimaan terbaik agar kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ibu tau kamu suka menulis, kenapa tidak mencoba untuk banyak menulis?”
“Ibu mau Naila mencari uang sebagai penulis?” tanyaku.
“Iqra’ Naila. Iqra’. Ibu hanya ingin kamu menulis lebih banyak cerita agar kamu bisa mengasah kemampuanmu sehingga kamu bisa menciptakan cerita dengan versi yang terbaik. Tujuannya bukan untuk mencari uang, tapi agar banyak orang yang akan termotivasi dengan karya-karyamu. Itu artinya kamu bisa memberikan manfaat untuk orang lain melalui tulisan-tulisanmu. Paham?”
Aku membisu mendengar ucapan ibu. Cairan bak embun menetes lagi dari sudut netra. Ya Rabbi. Penjelasan ibu menancap sangat dalam di pikiranku, meluluhkan hati yang berkarat bagai besi. Selama ini aku hanya terlalu fokus dengan segala kekuranganku yang membuat diriku sendiri terkurung oleh rasa takut dan khawatir, membutakan mataku dari rasa nikmat yang sesungguhnya. Di desa yang kecil ini, aku memperoleh pelajaran yang tak bisa kuterima hanya dengan kedua tanganku, namun harus diterima dengan pikiran dan hatiku.
Terima, hadapi, dan pelajari setiap kepingan takdir dengan penerimaan terbaik berupa rasa ikhlas dan terus berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Akan kusimpan pelajaran ini dengan folder khusus di hati dan pikiranku sampai akhir hayatku.(DEW)
BIOGRAFI PENULIS

Amroh Mustaidah
Amroh Mustaidah seorang mahasiswi aktif prodi Tadris Bahasa Inggris. Untuk mengenal lebih jauh tentang penulis dapat menghubungi e-mail pribadinya [email protected]

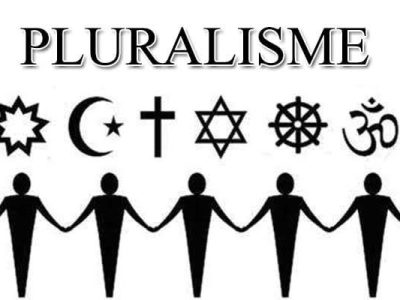













No comments